Aksara
Rajapatni.com: SURABAYA – Nama Eduard Douwes Dekker (Multatuli) tidak asing di telinga, meski ia adalah orang asing di eranya (1820 – 1887). Ia dikenal sebagai penulis Belanda, yang terkenal lewat novelnya “Max Havelaar” (1860). Isi novel itu mengecam penyalahgunaan kolonialisme di Hindia Belanda (Indonesia), yang berdampak pada sendi sendi kehidupan.

Karena itu nama Multatuli diabadikan sebagai nama nama museum, jalan, perpustakaan, dan taman baca.
Sebetulnya ada nama tokoh lain dalam periode waktu yang sama dan sebanding dengan Multatuli, yakni Herman Neubronner van der Tuuk. Ia terkenal sebagai peletak dasar linguistik modern yang berwujud beberapa bahasa daerah di Nusantara seperti bahasa Melayu, Jawa, Sunda, Batak Toba, Lampung, Kawi (Jawa Kuno), dan Bali. Tidak cuma bahasa, namun juga aksara daerahnya.
Aksara daerah menjadi kunci dalam meneliti bahasa, yakni untuk memahami bunyi dan pengucapan bahasa karena setiap aksara mewakili bunyi atau fonem tertentu dalam suatu bahasa, sehingga dapat diketahui cara pengucapan yang benar dan fonetik (bunyi) bahasa tersebut.
Dari hasil penelitian itu, Van der Tuuk bisa mendokumentasikan menjadi kamus kamus seperti kamus bahasa Lampung, Jawa dan Bali. Ia juga berupaya menyusun kamus bahasa Sunda, namun tidak berhasil diterbitkan secara resmi, melainkan terwujud dalam bentuk kumpulan catatan yang beraksara Cacarakan dengan penjelasan dalam bahasa Belanda, yang keberadaannya disimpan di Universitas Leiden, Belanda.
Dapat dimengerti bahwa ketika terkait dengan penelitian bahasa Kawi, yang penggunaan aktifnya antara abad 9 hingga 15, sementara penutur bahasa Kawi di era vander Tuuk di abad 19 sudah tidak ada, maka untuk mengetahui bunyi bahasa Kawi, Van der Tuuk mendasarkan penelitian bahasa Kawi pada sumber sumber prasasti yang bersifat tulis. Dari prasasti itulah, ia bisa mengenali bunyi dan pengucapan bahasa Kawi (Jawa Kuno).
Ringkasnya, Herman Neubronner van der Tuuk, yang dikenal sebagai peletak dasar linguistik bahasa bahasa daerah, menggunakan Aksara daerah untuk memahami Bahasa bahasa daerah yang ditelitinya.
Eduard Douwes Dekker (Multatuli) dan Herman van der Tuuk.

Ketika Multatuli melalui karya novel “Max Havelaar”, yang isinya mengecam penyalahgunaan kolonialisme di Hindia Belanda, yang berakibat pada sendi sendi kehidupan masyarakat negeri jajahan, termasuk adanya ancaman terhadap penggunaan bahasa daerah baik lisan maupun tulis, Van der Tuuk hadir dengan karya karya linguistik, yang berkontribusi pada pendokumentasian bahasa dan aksara daerah. Hasilnya adalah kamus kamus dan catatan catatan linguistik.
Hadirnya kolonialisme, termasuk hadirnya bahasa dan aksara asing khususnya Aksara Latin, tentu berpengaruh pada penggunaan bahasa dan aksara daerah. Ternyata terbukti nyata, Nusantara yang memiliki bahasa dan aksara daerah sendiri semakin tergeser oleh Aksara Latin dan bahasa asing.
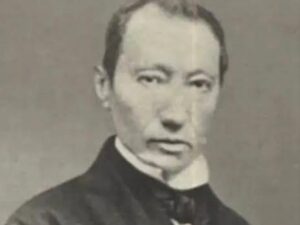
Herman van der Tuuk di periode zaman yang sama, abad 19, malah berhasil meneliti dan mengabadikan bahasa bahasa daerah dengan aksara sebagai alatnya.
Semangat Lokal
Semangat Lokal Van der Tuuk ini membangkitkan perlawanan secara kultural terhadap budaya kolonial yang masuk ke Nusantara. Meskipun ia masih berdarah Belanda (blasteran), Van der Tuuk turut “menyebarkan” semangat perlawanan terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Hal ini membuat posisinya menjadi isu kontroversial di kalangan masyarakat Eropa dan pejabat kolonial.
Isu kontroversial tentang Herman Neubronner van der Tuuk di kalangan masyarakat Eropa dan pejabat kolonial adalah perilaku dan pandangannya, yang dianggap menyimpang dari norma kolonial, seperti menentang cara berpakaian khas Belanda dan mendukung penggunaan bahasa daerah secara luas.
Van der Tuuk memang meneliti bahasa Batak, Lampung, Sunda, Jawa dan Bali. Hasil hasilnya cukup banyak. Yaitu penyusunan kamus bahasa Melayu, Jawa, Batak Toba, Lampung, dan Bali, serta menyusun buku tata bahasa Batak pertama, dan studi kekerabatan bahasa-bahasa Austronesia. Ia juga pertama kali mendokumentasikan tulisan dan kebudayaan di Batak, serta menginventarisasi naskah-naskah dan lontar di daerah-daerah seperti Bali.
Karya karya itu memberikan landasan kokoh untuk studi kebahasaan di Nusantara (Indonesia) dan berkontribusi besar pada pemahaman keberagaman bahasa dan budaya Indonesia, yang terus dihargai hingga kini.
Sayang, nama Herman N. Van der Tuuk belum umum dikenal di tengah masyarakat, kecuali di kalangan ahli bahasa (linguis).
Diabadikan Di Bali Sejak Era Kolonial

Selama ini masih ada satu tentang Van der Tuuk, yaitu untuk penamaan “Gedong Kirtya”, sebuah perpustakaan lontar di Singaraja, Bali, yang memang didirikan untuk mengenang jasa H.N. van der Tuuk, karena jasanya terhadap pendokumentasian bahasa dan budaya Bali.
Gedong Kirtya Bali ini sebenarnya didirikan pada tanggal 1928 oleh pemerintah kolonial Belanda di Singaraja, Bali. Ini sebetulnya masih tinggalan dari masa kolonial.
Lantas penghargaan apa dari pemerintah indonesia kepada Herman N. Van der Tuuk setelah kemerdekaan 1945 atas jasanya mendokumentasikan bahasa bahasa daerah?
Sejak tahun 2017, ada undang undang tentang Pemajuan Kebudayaan yang didalamnya ada Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) sebagaimana diatur pada pasal 5.
Dalam pasal itu ada objek Bahasa dan Manuskrip serta Seni, yang semuanya sudah menjadi objek perhatian dan penelitian Van der Tuuk di abad 19, yang keberadaannya telah dilindungi undang undang sejak 2017 untuk dilestarikan.


Mengenang Van der Tuuk adalah bagian dari upaya pelestarian Object Bahasa (daerah). Jejak Van der Tuuk ada di Surabaya, yakni berupa makam di pemakaman Eropa Peneleh Surabaya.
Bersambung, “Van der Tuuk adalah Surabaya (S.B)”. (PAR/nng).

